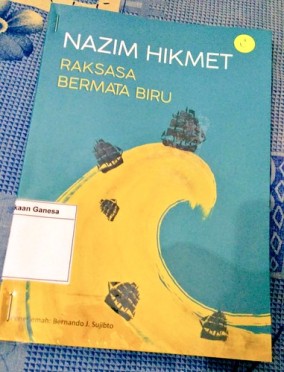
Sepertinya masih sangat jarang kita temui, atau bahkan mungkin belum ada sama sekali, karya sastra Turki dalam bentuk puisi diterjemahkan dan diterbitkan dalam bahasa Indonesia. Raksasa Bermata Biru karya Nazim Hikmet yang diterjemahkan oleh Bernando J. Sujibto ini bisa jadi yang pertama. Sebagai sebuah perkenalan kepada pembaca Indonesia, kumpulan puisi ini berisikan sejumlah tulisan yang memang tepat untuk memberitahukan tentang siapa seorang Nazim Hikmet.
Perkenalan dengan Hikmet ini dibuka dengan puisi berjudul Otobiografi, yang menceritakan tentang Nazim Hikmet secara keseluruhan: kapan ia lahir, di mana ia menimba ilmu, kejadian apa saja yang pernah dialaminya, kisah cintanya, sifat-sifatnya, kecenderungannya yang tidak tertarik pada kekuasaan maupun jabatan, juga kerendahan hatinya. Namun dari sekian banyak hal yang diceritakan melalui bait demi bait dalam Otobiografi, yang paling menarik adalah sifat-sifat sang penyair. Salah satu contohnya sebagaimana yang tersirat pada bait pertama:
“aku tidak akan kembali lagi ke kota kelahiran
aku tidak suka kembali ke belakang”
Dari dua baris ini tampak jelas bagaimana seorang Nazim Hikmet memandang masa lalu. Ia sama sekali tidak tertarik untuk menengok ke belakang, mengenang-ngenang kembali yang sudah lalu terutama asal-usulnya. Mungkin baginya tidaklah penting ia terlahir di mana dan bagaimana masa kecilnya. Mungkin yang penting baginya adalah apa yang saat ini dijalaninya.
Sifat Hikmet lain yang menarik adalah kemandiriannya, yang sedikit banyak memperlihatkan betapa tinggi harga dirinya, seperti yang dapat dilihat pada dua baris yang berbunyi:
“aku berbohong karena malu mengendalikan orang lain
aku berbohong demi tidak menyusahkan orang lain…”
Hikmet tak mengelak bahwa ia telah berbohong pada orang lain, tetapi itu dilakukannya agar ia tak perlu menyusahkan atau merepotkan orang lain, agar ia tak perlu meminta orang lain melakukan ini dan itu (maka mengendalikan). Jika membaca jalan hidup Hikmet sendiri yang dijabarkan pada bagian pembuka oleh Bernando J. Sujibto, maka ini tidaklah mengherankan. Jalan kesendirian yang ditempuh Hikmet ini juga terang ketika ia berkata di salah satu bait bahwa ia “tidak pergi ke mana orang pergi.” Hikmet bukanlah seseorang yang suka menggerombol dan mengikuti arus, ia lebih suka berjalan sendiri.
Bisa jadi, jalan kesendirian inilah yang membawa Nazim Hikmet pada pilihan ideologinya. Dengan memilih untuk menjadi seorang komunis, ia melawan arus di negerinya sendiri dan harus menanggung julukan pembelot. Hal tersebut disinggung dalam puisinya yang keenam di buku ini, yang diberi judul sesuai dengan pandangan pemerintah Turki pada saat itu terhadap dirinya, Pengkhianat Negara. Puisi ini menyajikan ironi, karena ketika di satu sisi pemerintah menganggapnya pengkhianat negara, di sisi lain mereka telah “menjual” negeri mereka sendiri kepada Amerika Serikat dan menyediakan tempat bagi pangkalan militer negeri Paman Sam. Hikmet secara terang-terangan menunjukkan siapa sebenarnya yang telah mengkhianati negara, dan siapa yang tidak.
Hikmet juga menyindir Amerika Serikat lewat puisinya Nelayan Jepang, sebuah puisi pilu yang ditujukan untuk mengingat tragedi uji coba bom hidrogen di tahun 1954. Pada puisi tersebut, Hikmet mengandaikan kapal di laut sebuah keranda berwarna hitam, siapa pun yang berada di sana pasti mati, dagingnya pasti membusuk, yang tertular pasti tak akan selamat. Uji coba semacam ini tentu sangatlah keji karena melibatkan dan mengorbankan banyak manusia tanpa pikir panjang dan tanpa pandang bulu. Ketika dalam satu baris Hikmet bertanya, “wahai manusia, di manakah kalian?”, sesungguhnya yang ia pertanyakan bukanlah di mana keberadaan manusia, tetapi keberadaan “akal sehat” dan “belas kasihan” mereka yang menciptakan senjata demikian.
Puisi-puisi Hikmet dalam buku ini yang menyindir pemerintahnya sendiri pun tidak sedikit. Ambillah contoh Rezim dan puisi berjudul 5 Oktober 1945. Dalam Rezim, ia berkisah tentang Presiden Adnan Menderes yang mengirimkan tentara panggilan untuk ikut bertempur di Perang Korea. Melalui pilihan kosakatanya (atau setidaknya yang digunakan oleh sang penerjemah, Bernando J. Sujibto) terasa jeritan pilu para prajurit yang dikirim bukan untuk membela negeri sendiri, melainkan ikut campur perkara negara lain demi aliansi politik. Di sisi lain, ironisnya, sang presiden bersenang-senang dan menikmati kekuasaannya, tubuhnya sehat, benaknya tak memikirkan mayat-mayat prajurit yang diutusnya.
Sementara itu, pada puisi 5 Oktober 1945, Hikmet mencurahkan kekesalannya kepada pemerintah lantaran abai terhadap rakyat. Negara membiarkan mereka kelaparan, kedinginan, kelelahan sampai mati (akibat kerja membanting tulang) dan berpisah (dengan keluarga dan orang-orang tercinta). Untungnya, kata Hikmat, rakyat belum sampai pada tahap saling membunuh. Untungnya lagi, rakyat biasa bukan tak mungkin punya kuasa atau daya untuk menunjukkan kepada pemerintah cara-cara kemanusiaan dan mencintai.
Bicara soal cinta, Nazim Hikmet tidak melulu berbicara tentang dirinya, perjuangan, maupun mengkritik ini-itu. Dalam kumpulan puisi Raksasa Bermata Biru ini, sang penyair juga berbicara soal cinta—suatu hal universal yang dirasakan oleh setiap insan—pada puisi berjudul Salju Membelai Jalanan misalnya. Selain cinta, sang penyair juga berbicara tentang kehidupan dan kematian. Pada puisi Tentang Kematian, Hikmet berkata kepada istrinya Hadijah Pirayende bahwa ia tidak tahu siapa di antara mereka yang akan lebih dulu mati dan kapan, di mana, serta bagaimana kelak mereka akan mati. Sedangkan dalam puisi berjudul Laut Malam Itu, Hikmet mengingatkan bahwa nafas (atau kehidupan) kita adalah pemberian Ilahi, maka dari itu jangan sampai kita lupa kepada sang Pencipta dan lupa bahwa yang abadi justru adalah kematian: kehidupan setelah kita mati.
Raksasa Bermata Biru secara langsung maupun tidak langsung merupakan otobiografi Nazim Hikmet sendiri, yang bercerita tentang riwayatnya, kisah cintanya, pilihan politiknya, kritik-kritiknya, juga apa yang diperjuangkannya. Setiap puisi tersaji dalam pilihan kata yang mengundang dan mengandung pilu, ironi, serta sendu. Hasil terjemahan Bernando J. Sujibto mampu menyalurkan ketiga rasa tersebut kepada pembaca, sehingga pembaca juga dapat mengenal nada dan gaya berbicara Hikmet pada bait-bait ciptaannya.
Selain dengan Nazim Hikmet sendiri, buku kumpulan puisi ini juga merupakan perkenalan pembaca Indonesia dengan perpuisian Turki. Pembaca Indonesia tentu sudah tidak asing lagi dengan karya-karya fiksi karangan Orhan Pamuk, Elif Shafak, atau O.Z. Livaneli, tetapi mungkin kita belum mengenal pujangga-pujangga Turki secara luas. Buku ini bisa menjadi jalan pembuka bagi diterbitkannya lebih banyak lagi karya-karya puisi dari negeri dua benua.
Rating: 3/5
Keren. Apa review ini sudah diinfokan ke penulisnya ?
terima kasih 😉
sayang penulisnya sudah meninggal. tapi saya rasa penerjemahnya sudah tahu :).
Ya maksud saya penerjemahnya. 👍 bagus bgt reviewnya..
makasih banget 😊😊😊
Halo dan salam kenal.
Ulasan buku puisinya keren, Mbak. Saat ini saya sedang membaca novel dari Turki karya Ece Temelkuran, dan ulasan di blog ini membuat saya semakin penasaran dengan sastra Turki.
Terima kasih, dan mampir kapan-kapan ke blog buku saya. 😁
Halo, salam kenal juga. Wah, sedang baca Ece Temelkuran ya? Saya dari dulu juga penasaran tapi belum sempat 😃.